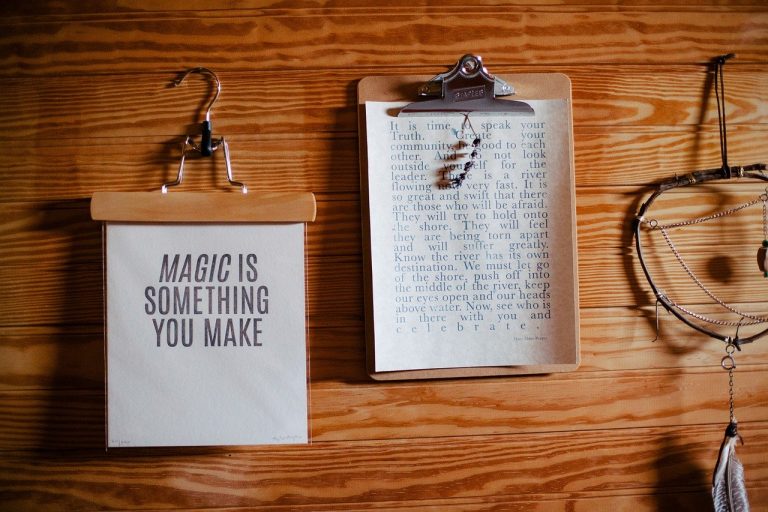Merawat Kemerdekaan Kita II
Delapan puluh tahun kemerdekaan adalah usia yang mengundang dua rasa: syukur dan waswas. Syukur, karena bangsa ini bertahan melewati gelombang kolonialisme, otoritarianisme, krisis ekonomi, hingga badai digital yang membelah-belah wacana dan ruang publik. Waswas, karena di seberang “jembatan emas”, meminjam bahasa Bung Karno, kita masih harus memilih: menuju dunia “sama rata sama rasa” atau “sama ratap sama tangis”. Kemerdekaan bukan ruang kosong; ia adalah jalan yang menuntut arah, etos, dan kompas moral. baca Merawat Kemerdekaan Kita I
Kompas itu, bagi Yudi Latif, berakar pada Pancasila yang dipersatukan oleh daya cinta kasih dan diwujudkan dalam kerja gotong royong; “pembantingan tulang bersama” untuk keadilan sosial. Di sini kemerdekaan bukan sekadar bebas dari, melainkan bebas untuk: untuk melayani, menolong, dan mensejahterakan sesama, dengan agama, budaya, dan politik bertemu dalam orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab. (pusdik.mkri.id, journal.iain-manado.ac.id)
Namun, gotong royong bukan jargon; ia menuntut tubuh, bahasa sikap, dan tata kelola. Di titik ini, Pdt. Zakarias A. Ngelow—teolog yang membaca perjumpaan kekristenan dengan pergerakan nasional, mengingatkan bahwa nasionalisme Indonesia lahir dari pergumulan multi iman dan multi budaya. Iman publik, kata beliau, dipanggil menjadi garam dan terang bagi cita-cita republik. Nasionalisme semacam ini bukan sentimentalitas simbolik, melainkan tanggung jawab etis untuk merawat kebangsaan secara oikumenis: memandang “yang lain” sebagai sesama, bukan ancaman. (Leimena, UKSW Repository, journal.actual-insight.com)
Sementara itu, Profesor Ishak Ngeljaratan, budayawan yang menubuhkan filsafat dalam keseharian—mengetuk kesadaran kita lewat etika Bugis-Makassar, siri’ na pacce: harga diri yang melahirkan empati, kesadaran akan martabat sendiri yang tak bisa dipisahkan dari rasa duka dan pedih orang lain. Kemerdekaan, bagi Prof. Ishak, adalah keberanian untuk memilih (dan memikul konsekuensi pilihan) serta kesetiaan kepada demokrasi sebagai ruang etik bersama. Di sini, estetika hidup—cara kita bertutur, bermusyawarah, berguyub—menjadi etika publik. (Gosulsel.com, Rumah Kampung Kota)
Menggenggam tiga suara ini, mari kita menafsir ulang makna “merdeka” pada tahun 2025. Apa artinya merawat kemerdekaan di tengah polarisasi, krisis kepercayaan, dan gempuran disrupsi digital?
Dari Hak ke Habitus
Sering kita merayakan kemerdekaan sebagai hak: hak bersuara, hak berkumpul, hak memilih. Padahal bangsa menjadi utuh bukan hanya oleh daftar hak, tetapi oleh habitus. Kebiasaan akal budi yang mengubah nilai menjadi laku. Gotong royong yang dibayangkan Yudi Latif adalah habitus: kebiasaan saling menolong yang ditopang cinta kasih lintas iman dan suku, sehingga keadilan sosial bukan proyek negara semata, melainkan praktik harian warga: di RT, pasar, pura, vihara, kelenteng, masjid, gereja, kampus, kantor, dan layar-layar gawai kita. (pusdik.mkri.id)
Habitus itu menuntut disiplin: jujur saat tak ada yang mengawasi, berhemat saat mudah konsumtif, menyimak sebelum berkomentar. Ia tumbuh dari rumah (yang mengajarkan malu mencurangi antrian), dari sekolah (yang menghargai proses, bukan hanya nilai), dari kantor (yang memuji integritas, bukan sekadar hasil jangka pendek). Kemerdekaan tanpa habitus adalah bendera yang gampang robek.
Dari Identitas ke Solidaritas
Di ruang digital, identitas mudah dikomodifikasi; kebhinekaan direduksi menjadi label, suku, cluster, bubble. Dalam situasi ini, kita perlu kembali pada pelajaran Pdt. Zakarias Ngelow: nasionalisme Indonesia lahir dari perjumpaan, tindakan lintas batas yang melihat sesama sebagai mitra peradaban. Oikumenisme menawarkan disiplin empati: berdiri di sisi orang lain untuk memahami ketakutannya, kebutuhannya, dan harapannya. Dari sini terbuka solidaritas: kita membela minoritas bukan demi “mereka”, melainkan demi “kita” yang ingin tetap menjadi bangsa. (Leimena, UKSW Repository)
Solidaritas bukan berarti menghapus perbedaan. Ia justru membutuhkan perbedaan agar gotong royong bermakna. Kita tak perlu selalu sepakat dalam doktrin, namun bisa bersekutu dalam kerja-kerja publik: memastikan anak-anak bermain dengan riang dari rumah hingga ruang ibadah, lingkungan bebas banjir, layanan kesehatan terjangkau, dan proses politik yang jujur.
Dari Euforia ke Etika
Prof. Ishak Ngeljaratan mengikat kemerdekaan pada etika dan estetika hidup: siri’ na pacce mengajarkan bahwa martabat diri tak sah jika acuh pada derita orang lain. Maka euforia seremoni 17 Agustus harus berkelindan dengan etika keseharian: tepat waktu, tidak korup, sopan di jalan, teliti dalam data, adil dalam menilai.
Demokrasi pun bukan sekadar pemilu lima tahunan, melainkan kesanggupan berdamai dengan perbedaan, mengakui cela, dan memperbaiki diri. Etika yang peka melahirkan kebijakan yang tangguh: tata ruang yang menjaga kampung dari longsor dan banjir, pendidikan yang melatih nalar bukan hafalan, inovasi yang mengakar pada kearifan lokal (air, pangan, energi), dan transformasi digital yang menolak menjadi “penjajah baru” melalui hoaks, perundungan, atau eksploitasi data.
Dari Narasi ke Kinerja
Refleksi ini tidak boleh berhenti di kata-kata. Takdir kita dua dekade ke depan ditentukan oleh cara kita mengubah narasi menjadi kinerja. Yudi Latif menyebut “revolusi mental” bukan proyek vertikal, melainkan restorasi gotong royong dalam ekosistem yang nyata. Itu berarti menghubungkan Pancasila dengan tata kelola: data terbuka, akuntabilitas anggaran, partisipasi publik, dan penghargaan atas kerja kolaboratif di birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. (Kementerian PANRB)
Di aras masyarakat, kinerja berarti: koperasi digital yang adil, UMKM naik kelas dengan ekosistem logistik dan pembayaran yang inklusif, riset kampus yang menyatu dengan problem riil, startups yang memecahkan isu agrikultur, kesehatan, dan pendidikan. Di aras budaya, kinerja berarti memelihara bahasa daerah, memuliakan kesenian, dan memperlebar akses bagi seniman dan anak muda untuk berkarya, tanpa gatekeeping yang mempersempit bakat.
Dari Ketakutan ke Harapan
Tantangan 2025 ini jelas: kesewenang-wenangan pemerintah, oknum kelompok mayoritas yang semena-mena, jurang kaya-miskin, polarisasi, perubahan iklim, dan disrupsi AI. Semua ini mudah membangkitkan rasa cemas di ruang publik dan jagat maya. Namun kemerdekaan adalah keberanian untuk berharap secara rasional. Harapan bukan optimisme kosong; ia perhitungan cermat antara sumber daya dan niat baik. Jika negara menyediakan rambu (hukum yang adil), warga membawa mesin (etos kerja), komunitas menyuplai bahan bakar (kepercayaan sosial). Tanpa kepercayaan, mesin negara macet; tanpa etos, bahan bakar menguap.
Harapan juga berwujud kecil-kecil: subsidi buku untuk anak-anak sekolah, taman baca di gang sempit, les matematika dan bahasa Inggris gratis di desa-desa, klinik hukum gratis di kampus, komunitas peduli lingkungan, kelas literasi digital di rumah ibadah. Di sanalah Pancasila bernapas; di sanalah teologi publik bertumbuh; di sanalah siri’ na pacce menemukan tubuhnya.
Pilihan Merawat Kemerdekaan Kita
Politik Kebaikan. Kurangi kebencian, tambah transparansi. Politik bukan arena saling meniadakan, melainkan ruang deliberasi publik seperti yang dibayangkan Jurgen Habermas, dimana argumen menggantikan amarah, dan diskusi berbasis data menyingkirkan dendam. Kritik hadir untuk mengoreksi, bukan menghabisi. Demokrasi menjadi sarana memperbaiki, bukan menghancurkan.
Ekonomi Perawatan. Ukurlah keberhasilan bukan hanya dari pertumbuhan GDP, tetapi dari menurunnya kemiskinan struktural, menguatnya perlindungan sosial, dan pulihnya ekologi. Ekonomi tidak boleh hanya mengejar akumulasi, tetapi harus merawat kehidupan. Seperti ditekankan Yudi Latif, ekonomi Pancasila harus mengedepankan gotong royong, bukan predatorisme pasar.
Budaya Perjumpaan. Rawat ruang-ruang lintas iman, lintas identitas. Perkuat seni sebagai jembatan makna. Jadikan bahasa sebagai rumah bersama, bukan senjata. Seperti diingatkan Ishak Ngeljaratan, kebudayaan adalah arena perjumpaan yang membebaskan, bukan sekadar perbedaan yang mengeras. Dialog, bukan monolog; keragaman, bukan fragmentasi.
Delapan dekade kemerdekaan adalah pencapaian besar, tetapi sekaligus pengingat: kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati, ia harus dirawat. Dalam perjalanannya, bangsa ini telah melalui banyak ujian: pergulatan ideologi, dinamika ekonomi, dan benturan identitas. Kini, tantangan kita berbeda sebab kita bukan lagi merebut kemerdekaan dari penjajah, melainkan menjaga agar demokrasi tidak tereduksi menjadi sekadar prosedur, agar ekonomi tidak menjadi mesin pemiskinan yang rakus, dan agar kebudayaan tidak tercerabut dari akar persaudaraan. Karena itu, kita memerlukan tiga laku sederhana untuk merawat kemerdekaan di usia 80 tahun: Politik Kebaikan, Ekonomi Perawatan, dan Budaya Perjumpaan.
Pada akhirnya, kemerdekaan adalah pilihan harian. Setiap pagi, kita menyeberangi jembatan emas itu kembali yaitu dengan kata-kata yang kita pilih, dengan tautan yang kita bagikan, dengan keputusan yang kita buat di kantor, kelas, atau pasar. Yudi Latif mengingatkan kompas gotong royong; Pdt. Zakarias A. Ngelow menyalakan lampu oikumenisme; Prof Ishak Ngeljaratan menegakkan cermin siri’ na pacce. Tiga suluh ini cukup untuk menerangi jalan, jika kita bersedia berjalan.
Indonesia tak butuh pahlawan tunggal; Indonesia butuh warga yang cakap menanggung kebebasan. Merdeka bukan kepunyaan kemarin, melainkan pekerjaan hari ini. Dan pekerjaan itu, sebagaimana semua karya baik, dimulai dari hal-hal kecil yang dikerjakan dengan kesetiaan.
Selamat 80 tahun, Indonesia. Semoga kita selalu memilih jalan “sama rata sama rasa”, dan menolak “sama ratap sama tangis” bukan karena tak ada badai, melainkan karena kita siap bergandengan tangan melewatinya.